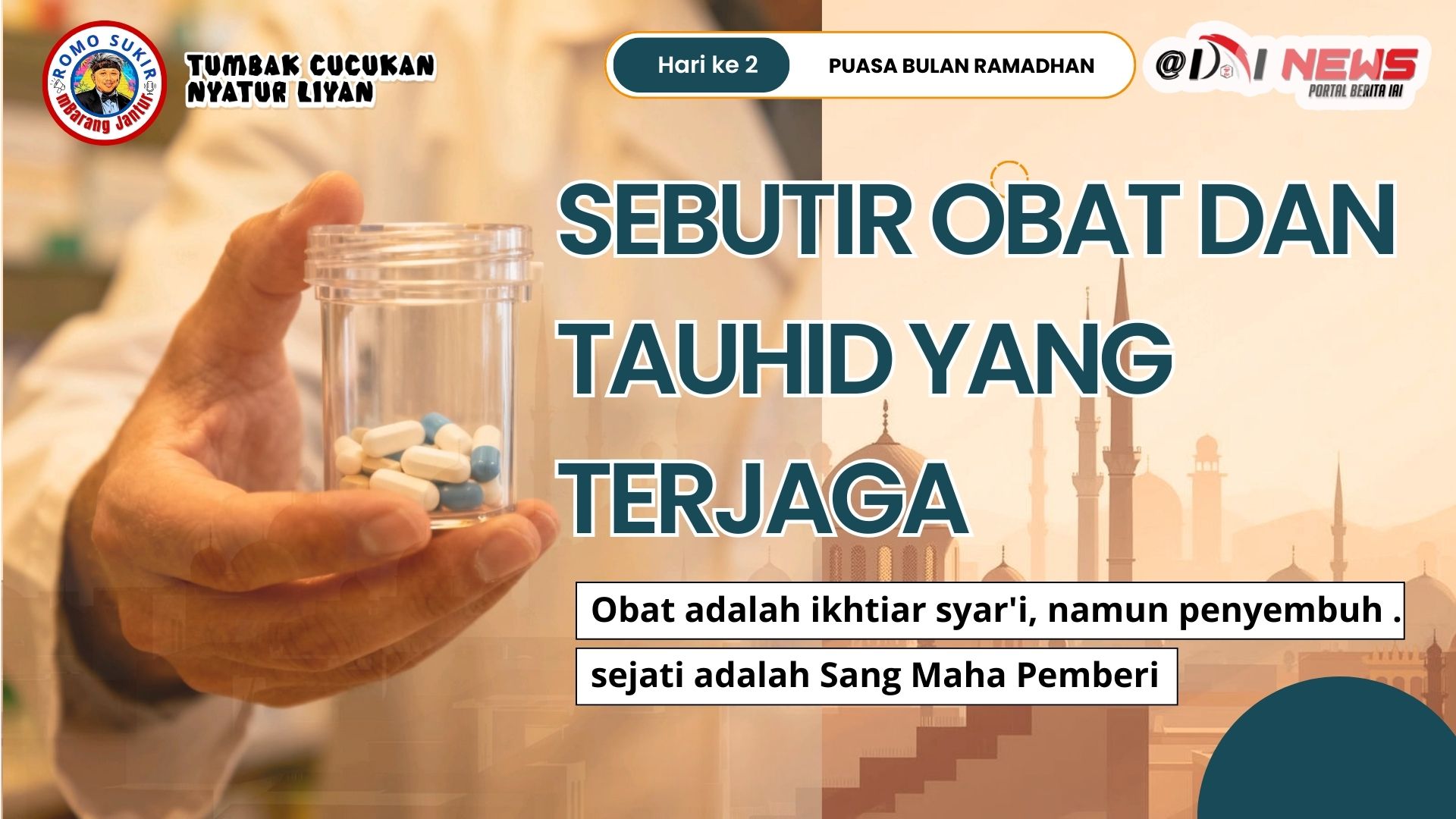SEBAGAI seorang apoteker dan akademisi yang berkecimpung dalam dunia farmasi, saya menyambut baik pernyataan Menteri Agama Nasaruddin Umar mengenai kewajiban sertifikasi halal penuh untuk produk farmasi yang akan berlaku mulai 17 Oktober 2026.
Kebijakan yang diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 ini merupakan langkah maju dalam perlindungan konsumen di Indonesia.
Dari sudut pandang profesi kefarmasian, sertifikasi halal bukan sekadar pemenuhan kewajiban religius, melainkan juga bagian dari upaya memastikan mutu, keamanan, dan kebersihan produk obat yang dikonsumsi masyarakat.

Namun, di balik sambutan positif tersebut, tantangan terbesar yang saya lihat sebagai apoteker adalah kompleksitas rantai pasok bahan baku farmasi.
Berbeda dengan produk makanan, obat-obatan seringkali menggunakan bahan aktif yang berasal dari berbagai sumber, termasuk enzim, gelatin, dan eksipien yang berpotensi berasal dari hewani.
Industri farmasi harus melakukan penelusuran menyeluruh terhadap seluruh bahan baku dan proses produksi.
Di sinilah peran apoteker sangat krusial, karena kami memahami seluk-beluk formulasi obat dan dapat memberikan rekomendasi alternatif bahan baku halal tanpa mengorbankan khasiat dan keamanan produk.
Untuk mengatasi kompleksitas tersebut, sinergi antarlembaga menjadi mutlak diperlukan.
Saya mengapresiasi pernyataan Menag mengenai pentingnya sinergi antara BPOM, BPJPH, Kementerian Agama, dan Lembaga Pemeriksa Halal.
Sebagai tenaga kesehatan yang bersinggungan langsung dengan regulasi obat, saya melihat bahwa kolaborasi ini akan mempercepat proses adaptasi industri.
BPOM yang telah memiliki pengalaman panjang dalam standardisasi dan pengujian keamanan obat, bersama BPJPH dengan kompetensinya dalam aspek kehalalan, dapat menciptakan standar ganda yang saling melengkapi.
Digitalisasi sistem perizinan dan pengawasan yang disebutkan Menag juga akan sangat membantu apoteker dalam memverifikasi status kehalalan produk yang beredar di apotek.
Lebih jauh lagi, konsep halalan thayyiban yang diangkat Menag Nasaruddin ternyata sejalan dengan prinsip dasar kefarmasian.
Dalam praktik sehari-hari, apoteker selalu mengedepankan aspek keamanan, khasiat, dan mutu obat.
Sertifikasi halal dengan pendekatan thayyiban (baik dan menyehatkan) memperkuat komitmen industri farmasi untuk menghasilkan produk yang tidak hanya halal secara agama, tetapi juga aman secara ilmiah.
Ini menjadi nilai tambah yang signifikan, karena konsumen tidak perlu ragu lagi terhadap kualitas produk yang mereka konsumsi.
Menarik untuk dicermati bahwa sertifikasi halal pada produk farmasi, termasuk vaksin, justru dapat menjadi unique selling point di pasar global.
Indonesia dengan populasi muslim terbesar dunia memiliki potensi besar menjadi pusat industri farmasi halal.
Sebagai apoteker dan akademisi, saya melihat peluang ini sebagai momentum untuk mendorong riset dan pengembangan produk farmasi halal dalam negeri.
Jika dikelola dengan baik, industri ini tidak hanya memenuhi kebutuhan domestik tetapi juga berpeluang ekspor ke negara-negara muslim lainnya, sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi tenaga kefarmasian baik tenaga vokasi farmasi, apoteker, maupun apoteker spesialis.
Pada akhirnya, kebijakan ini membuka peran baru bagi apoteker sebagai garda terdepan dalam edukasi masyarakat.
Kita perlu aktif memberikan pemahaman bahwa sertifikasi halal pada obat tidak mengurangi efektivitas terapi, justru menambah jaminan mutu.
Program Sehati yang difasilitasi pemerintah untuk UMKM juga patut diapresiasi, namun perlu dipastikan bahwa produk farmasi skala kecil tetap memenuhi standar keamanan yang ketat.
Sinergi antara pemerintah, industri, dan tenaga kesehatan seperti apoteker akan menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan ini demi terwujudnya perlindungan kesehatan masyarakat yang holistik.***